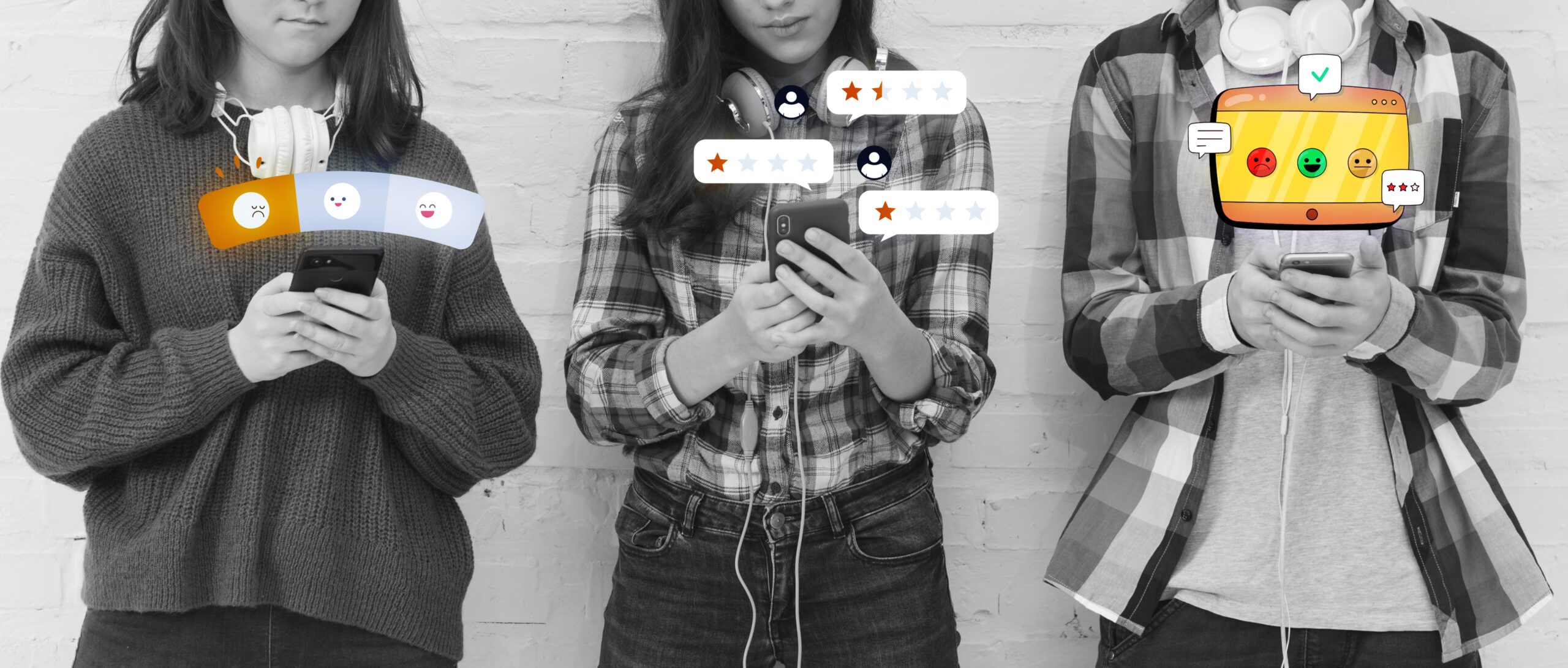Hari ini, politik tidak lagi hadir lewat diskursus panjang atau debat gagasan ideologi. Politik sekarang hadir lewat layar gawai dalam bentuk potongan video 30 detik (klip), meme, potongan pidato yang digeser maknanya, konflik yang dapat dibesarkan atau dikecilkan melalui persepsi konten dan mengambil kesimpulan melalui kolom komentar. Kita menyaksikan ini sambil rebahan, sambil menggulir layar tanpa henti. Tertawa, marah, membagikan, lalu lanjut ke konten berikutnya.
Tanpa sadar, banyak anak muda berusia produktif tidak lagi berperan sebagai warga negara yang aktif berpikir dan kritis, tetapi berubah menjadi penonton politik. Kita merasa “melek politik” karena sering melihatnya di media sosial, padahal yang kita konsumsi sering kali hanyalah permukaannya, persepsi kita terlalu memakan isi kepala.
Pertanyaannya sederhana: apakah kita benar-benar memahami politik atau hanya menikmatinya sebagai hiburan?
Politik dalam 30 Detik dan Kuasa Algoritma
Media sosial bekerja dengan satu logika utama: atensi. Algoritma tidak peduli mana konten yang paling benar, paling adil, atau paling berdampak bagi masa depan bangsa. Algoritma hanya peduli satu hal: konten mana yang membuat kita tidak berhenti menggulirkan layar.
Akibatnya, politik dipaksa masuk ke format yang sempit. Isu kompleks seperti kebijakan publik yang justru tidak berpihak pada publik, ketimpangan sosial ekonomi atau bahkan reformasi birokrasi dipotong menjadi slogan singkat dan narasi emosional. Hal sederhana mengalahkan yang akurat. Yang provokatif mengalahkan yang reflektif. Kita tidak lagi seutuhnya paham pada suatu diskursus.
Penelitian menunjukkan bahwa algoritma media sosial cenderung memperkuat konten yang memicu emosi kuat seperti marah, takut, atau fanatisme, karena emosi tersebut meningkatkan engagement (Tufekci, 2018). Dalam konteks kehidupan berbangsa, ini berbahaya. Anak muda akhirnya membangun opini bukan dari pemahaman utuh, tetapi dari potongan-potongan narasi yang dikurasi mesin. Di titik ini, influencer, buzzer, dan akun anonim sering kali lebih dipercaya daripada institusi resmi atau kajian akademik, kita dengan sadar melihat matinya sebuah “kepakaran”. Politik berubah menjadi persoalan siapa yang paling ramai, bukan siapa yang paling benar.
Demokrasi yang Digerakkan oleh Dopamin
Setiap like, share, dan komentar memicu pelepasan dopamin (zat kimia dalam otak yang berhubungan dengan rasa senang dan kecanduan). Menurut Montag & Diefenbach (2018) Media sosial secara desain memang dibuat adiktif. Masalahnya ketika publik dikuasai dopamin dan kemudian ini masuk ke ranah politik, demokrasi ikut berubah bentuk.
Politisi mulai berbicara dengan bahasa algoritma. Konten dibuat agar viral, bukan agar bermakna. Pernyataan kontroversial sering lebih efektif daripada membahas kebijakan secara matang. Drama lebih laku daripada kerja senyap.
Dalam kondisi seperti ini, demokrasi tidak runtuh karena kudeta atau senjata, tetapi karena kehilangan perhatian publik. Diskursus publik yang seharusnya rasional dan deliberatif bergeser menjadi kompetisi atensi. Politik tidak lagi soal gagasan jangka panjang yang berpihak pada masyarakat rentan atau publik secara luas, tetapi soal siapa yang paling sering muncul di linimasa, singkatnya, sekali lagi kita secara sadar melihat mati nya sebuah “kepakaran”. Seperti yang dikatakan Neil Postman (1985) jauh sebelum era TikTok, ketika politik berubah menjadi hiburan, maka substansi akan selalu kalah oleh sensasi.
Echo Chamber dan Matinya Diskusi Rasional
Masalah lain yang tidak kalah serius adalah echo chamber. Algoritma cenderung menyajikan konten yang sejalan dengan pandangan kita sebelumnya, pengguna media sosial secara tidak sadar terus dibuat yakin dengan pandangannya berdasarkan konten yang secara terus-menerus memili satu pandangan dengannya. Kita tidak kemudian dipertemukan dengan sudut pandang berbeda secara sehat, suatu hal yang tidak sejalan dibuat menjadi salah. Akibatnya, media sosial terasa seperti ruang yang sempit dan bising.
Penelitian Sunstein (2017) menunjukkan bahwa echo chamber memperkuat polarisasi dan membuat individu semakin yakin bahwa pandangannya adalah satu-satunya kebenaran. Dalam konteks anak bangsa, ini terlihat jelas: perbedaan pilihan politik sering berubah menjadi serangan personal, diskusi berubah menjadi adu identitas, bukan adu argumentasi yang membuat kita seharusnya bijak dalam melihat kekurangan pemangku kebijakan publik dalam mengambil keputusan.
Kita lebih cepat membela “kubu” daripada memeriksa data. Lebih cepat marah daripada berpikir. Lebih sibuk menang debat daring daripada memahami persoalan nyata.
Jika kondisi ini dibiarkan, dampaknya serius: kelelahan politik, sinisme terhadap negara, dan apatisme terhadap demokrasi. Anak muda tidak benar-benar apolitis, mereka hanya lelah dengan politik yang terasa gaduh tapi hampa. Hal ini dapat menurunkan partisipasi publik dalam menjalankan sebuah kebijakan, masyarakat hanya menjadi pembayar pajak tanpa mengetahui ke mana pajak ini dikelola.
Negara yang Hadir di Layar tapi Absen dalam Pendidikan Digital
Ironisnya, negara sering kali baru hadir di media sosial Ketika suatu hal baru ramai, tidak serta-merta memitigasi sebuah persoalan. Konten pemerintah yang rapih, visual menarik, tapi miskin edukasi kritis, hanya sebatas foto mengepalkan tangan. Literasi digital belum benar-benar diposisikan sebagai agenda kebijakan publik yang serius.
Padahal banyak riset menegaskan bahwa kualitas demokrasi di era digital sangat bergantung pada kemampuan warga untuk berpikir kritis terhadap informasi (Guess et al., 2020). Tanpa itu, media sosial justru menjadi alat manipulasi massal.
Negara, platform digital, dan masyarakat seharusnya berbagi tanggung jawab. Media sosial tidak mungkin dihapus, tetapi dampaknya bisa dikelola. Pendidikan politik dan literasi digital harus bergerak lebih cepat daripada algoritma. Negara semestinya lebih berkuasa dalam meregulasi aplikator media sosial agar Masyarakat terlindungi data nya dan ditajamkan pikirannya.
Dari Reaksi ke Refleksi
Sebagai anak bangsa yang hari ini hidup di dunia yang sangat mudah terhubung dan juga sangat mudah dipengaruhi. Kita tidak kekurangan informasi, kita kekurangan jeda untuk berpikir. Sudah banyak tulisan yang membahas tentang efek negatif adiksi media sosial namun kita tetap terasa candu untuk terus menggulirkan layar menuju pembusukan berpikir.
Masa depan demokrasi tidak ditentukan oleh seberapa viral konten politik hari ini, tetapi oleh seberapa dalam kita mau memahaminya. Karena hanya dengan memahami kita dapat mencegah diri ini untuk tidak terus terseret dalam arus apolitis yang membuat kita secara tanpa sadar tidak lagi berpikir kemana arah bangsa ini, bagaimana kebijakan publik berpihak dan mau bermanfaat kepada masyarakat luas.
Politik seharusnya kembali menjadi ruang refleksi, bukan sekadar reaksi. Dari menggulirkan layar tanpa henti menuju kesadaran digital. Dari penonton kembali menjadi warga negara.
Karena demokrasi yang sehat bukan hanya soal kebebasan berbicara, tetapi juga kemauan untuk berpikir lebih pelan di tengah dunia yang bergerak terlalu cepat.